"Aku pulang," samar suara khas Pandu menyelinap ke indera pendengarku.
"Neng, kamu di mana?" kembali suara Pandu terdengar tapi mataku masih terlalu berat untuk membuka. Lagipula tidak mungkin itu Pandu karena dia baru akan kembali beberapa hari lagi. Seperti biasa, dia harus mengunjungi lokasi untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan yang direncanakannya. Kali ini dia harus ke Kepulauan Anambas.
"Hei," kali ini suara Pandu tidak lagi terdengar samar. Suamiku seakan berada di sampingku yang sedang tidur di daybed dekat jendela ruang tengah rumah kami, "Capek banget, ya?" Kali ini tidak hanya suara tetapi juga belaian lembut di kepalaku.
"Kang," aku mengerjapkan mata beberapa kali untuk mengusir kantuk yang masih memberati mataku, "Kamu kok ada di sini?"
"Harusnya aku ada di mana?"
"Anambas. Kerja?" Aku menurunkan kaki sambil menegakkan punggung dan mendudukkan diriku.
Pandu tertawa sambil menarikku ke dalam pelukannya, "Sementara besok Ramadan?"
Aku mengangkat kepala dan menatapnya, "Kamu yakin kalau kamu Kang Pandu aku?"
"100 persen," Pandu mencium bibirku dengan lembut, "Masih nggak percaya?"
"Percaya. Tapi kamu, kan, biasanya menomor satukan pekerjaan."
"Hm," dia bergumam sambil menggosokkan ujung hidung ke telingaku, "Kadang-kadang. Nggak selalu. Aku juga belajar kalau ada yang harus dinomor satukan selain pekerjaan."
"Aku?"
"Keluarga," dia tersenyum lebar lalu menangkupkan kedua tangan di wajahku, "Kamu capek banget, ya?"
Aku menarik napas panjang, "Capek banget? Nggaklah. Kecapekan mungkin tapi nggak sampai banget."
"Kamu yakin? Ini bukan pertama kalinya aku pulang dan nemuin kamu ketiduran tanpa sempat ganti pakaian."
"Ah," aku mengangkat tangan sambil memperhatikan penampilanku. Kemeja sutra putih yang aku padukan dengan celana hitam dan jaket berwarna wilis yang senada dengan flat shoes yang seharian aku kenakan ketika berada di toko dan menyambangi kafe milik Pandu, "Tadi aku mau ganti pakaian tapi terus ketiduran."
"Sandina mana?"
"Tidur," aku melirik baby monitor yang ada di atas meja, "Nyenyak banget tidurnya. Udah dari sejak di jalan pulang."
"Aku ke kamar Sandina dulu," Pandu mencium keningku. Sambil menguap aku memperhatikan Pandu yang berlalu menuju kamar Sandina, anak pertama kami yang sekarang hampir berusia dua tahun.
Hampir tidak ada yang berubah bahkan menjelang ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Biro arsitek Pandu semakin besar dan itu menyebabkan dia harus terbang ke berbagai kota dan negara entah untuk meeting atau mengecek lokasi. Kabar baiknya sekarang dia lebih banyak meluangkan waktu untuk pulang. Dia berusaha untuk kembali setiap Jumat dan menghabiskan akhir pekan di rumah atau memintaku dan Sandina mengunjunginya. Walau sejujurnya aku cukup yakin Pandu melakukan itu lebih karena merindukan Sandina dibandingkan merindukanku.
"Gimana kalau kita pindah ke Jakarta?" Tiba-tiba Pandu sudah kembali berdiri di ambang pintu kali ini dengan membawa dua gelas berisi air mineral.
Aku memilih untuk menatapnya lama sebelum menjawab pertanyaannya, "Jakarta nggak pernah jadi rumah buat kita. Kamu tahu itu, kan?" Aku mengambil gelas yang diulurkannya.
"Aku tahu tapi rasanya sekarang lebih nyaman kalau kita tinggal di Jakarta."
"Kenapa?"
"Ada lebih banyak jadwal penerbangan yang bisa aku pilih."
"Cuma karena itu?"
Pandu menghabiskan air mineral sebelum menjawab pertanyaannya, "To be truth, I don't know, La. Kemungkinan itu muncul di kepalaku gitu aja."
"Tapi kenapa?"
"Aku capek jauh dari kamu. Jauh dari Sandina. Tinggal di Jakarta bakal bikin jadwal aku lebih fleksibel dan..."
"Gimana dengan My Ex-Boyfriend? Gimana dengan kafe kamu?"
"Aku nggak tahu. Aku belum mikir sampai ke situ. Ide itu baru kepikiran dan aku pengin diskusiin sama kamu."
"Diskusi tentang gimana cara terbaik aku ngebuang semua yang aku punya? Hidup aku di sini, Kang."
"Iya. Tapi," mulutnya membuka dan menutup beberapa kali sebelum akhirnya dia melanjutkan ucapannya, "Aku nggak yakin aku bisa ngelewatin momen-momen besar Sandina."
"Selama ini aku selalu ngirimin videonya ke kamu, Kang."
"Di situ masalahnya, La. Aku melewatkan semua momen Sandina dan cuma ngelihat lewat video. Pas pulang dan ngelihat secara langsung aku nggak bisa bohong kalau ada perasaan sedih. Harusnya aku bisa ngelihat momen itu secara langsung bukan lewat video."
"Kalau kita pindah ke Jakarta kamu yakin nggak akan ngelewatin satu momen pun?"
Pandu kembali mengangkat bahunya, "Aku nggak tahu"
"Kang, please, cukup dengan jawaban nggak tahu. Ini ide kamu."
"Aku benar-benar nggak tahu, La!" Suara Pandu meninggi tapi dengan cepat dia segera meminta maaf melalui matanya yang diselimuti rasa bersalah.
Aku menarik napas panjang sesaat sebelum berdiri dan berlalu menuju dapur untuk mengisi kembali gelasku sembari menenangkan diri. Kami sama-sama capek dan pertengkaran adalah hal terakhir yang aku dan Pandu inginkan.
"Illa, aku minta maaf," Pandu menyusulku ke sepen, "Kita lupain aja ide itu. Mungkin seharusnya aku pikirin dulu masalah itu matang-matang sebelum ngajak kamu diskusi."
"Kang," aku melepaskan jaket wol yang aku kenakan lalu menyampirkannya di stool, "Aku tahu kenapa ide itu muncul. Aku juga tahu kalau kondisi kita sekarang sama sekali bukan kondisi yang sempurna. Tapi tiap keluarga punya cerita masing-masing dan mungkin ini cerita keluarga kita. Nggak selalu bareng tapi bukan berarti ikatan keluarga kita nggak kuat."
Biasanya Pandu yang menarikku ke dalam pelukannya tetapi kali ini aku yang melakukannya. Pelan aku menarik pria itu ke dalam pelukan lalu mengalungkan lenganku di lehernya, "We'll be fine, Kang."
"We will," dia menatapku tajam sebelum menyapukan bibirnya di bibirku.
"Mulai sekarang aku nggak bakal ngirim video Sandina lagi ke kamu. Aku bakal tetap ngirim video atau foto lucu Sandina tapi untuk momen-momen besarnya, aku pengin kamu lihat pertama kali saat kamu pulang."
"Ide bagus! Kenapa nggak kepikiran sama aku, ya?"
Dalam pelukannya aku tertawa dan tepat ketika Pandu akan kembali menciumku terdengar suara tangisan Sandina.
"Duty call," aku melepaskan pelukan dan bergegas menuju kamar Sandina sementara di belakang Pandu tertawa dan beberapa saat kemudian segera menyusulku.
Mungkin keluarga kami tidak sempurna tapi ini yang terbaik untuk saat ini.
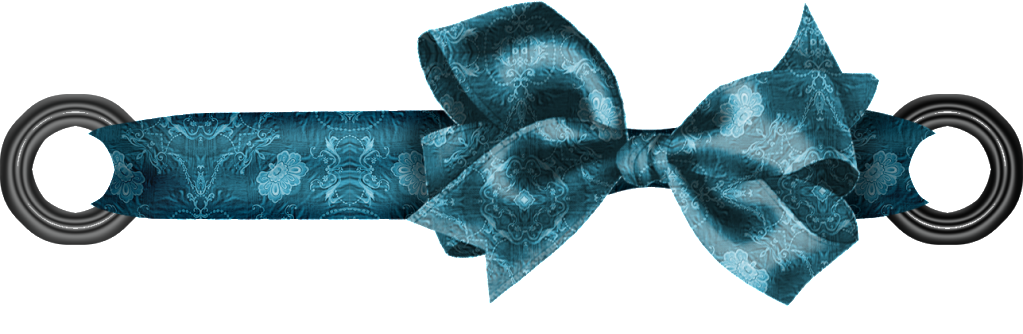


Kak, aku suka banget karya kakak yang ini
ReplyDeleteKak, aku suka banget karya kakak yang ini
ReplyDelete