Merah.
Patuh aku memelankan laju mobilku
hingga sempurna berhenti. Memilih menunggu lampu hijau, tidak ada gunanya
menerobos lampu merah. Lagipula tidak ada yang menunggu kepulanganku hingga aku
harus bergegas
Samar, radio yang aku nyalakan
untuk membunuh sepi mengalunkan sebuah lagu. Entah lagu apa, aku tidak update urusan music. Untukku music
berhenti pada era 90-an. Menunggu, aku
mengalihkan pandanganku, jauh ke luar jendela mobilku. Pemandangan khas lalu
lintas kota sore hari.
Gerimis. Hari ini gerimis juga
menemani hari, seperti kemarin. Aku menyukai aroma khas hujan, tapi akutidak
pernah suka dengan efek hujan. Mengembalikan kenangan yang seharusnya
dilupakan.
Entah karena hujan, entah karena
aku memang ingin mengingatnya, perlahan tugu Pancoran berubah menjadi jam
gadang, landmark kotamu, Bukittinggi,
tempat kita kemarin bertemu.
Aku belum pernah ke kotamu,
setidaknya hingga kemarin, tapi empat tahun kebersamaan kita membuatku hapal
dengan pasti setiap sudut kota itu, kotamu.
Jam gadang yang menjadi landmark kotamu. Denah dasar seluas 13 x
4 meter, tinggi 26 meter. Memiliki 4 jam dengan diameter 80 cm. Jam yang di
datangkan langsung dari Rotterdam, Belanda. Kembaran yang sempurna dari Big Ben
yang menjadi landmark kota London. Aku menghapal semua detail
tentang jam ini, karena kamu selalu bercerita dengan bangganya.
Pasar Atas yang terletak di
selatan Jam Gadang dan selalu ramai dengan wisatawan yang berbelanja. Setiap
kali bercerita tentang pasar ini kamu akan selalu mengingatkanku untuk menawar
separuh harga dari yang ditawarkan oleh penjual. Katamu, memang sudah menjadi
ciri pasar itu untuk tawar menawar sebelum terjadi transaksi dan bukan rahasia
umum pedagang membuka harga dengan dua kali lipat harga sebenarnya. Dan kamu
selalu mengakhiri ceritamu dengan menertawakanku, aku yang tidak bisa menawar,
terbiasa untuk langsung menerima harga yang disebutkan oleh penjual.
Jajaran tenda sate Padang yang
menjadi makanan kesukaanku. Setiap kali aku bilang aku ingin makan sate Padang,
seketika kamu akan tersenyum dan mengatakan bahwa di kotamu, tidak perlu
mengucapkan sate Padang, sate yang ada di kotamu ya sate Padang, tidak ada
pilihan sate yang lain.
Ya, aku menghapal setiap sudut
kotamu dengan baik.
Dan ketika kemarin aku memutuskan
untuk ke kotamu, aku seakan pulang. Aku menghapal kota itu dan mengenali
aromanya. Tapi mungkin itu karena kamu. Sudah lama kamu menjadi rumahku,
tempatku untuk berpulang.
Berbulan sejak kepulanganmu ke
kota itu, hanya pesan singkat yang menjembatani ribuan kilometer jarak di
antara kita. Pesan singkat yang sangat singkat. Tidak ada kata cinta, tidak ada
kata rindu, tidak ada kalimat mesra. Selalu kamu hanya membalas pesanku dengan
satu kalimat pendek.
“Bapak masih belum memberi lampu hijau. Sabar ya Mas.”
Berapa lama aku harus menunggumu?
Dan terakhir kali kamu mengirimkan pesan singkat padaku adalah sebulan yang lalu. Kemudian kamu menghilang, tanpa kabar.
Sebelum aku gila karena rindu
kepadamu, aku memutuskan untuk ke kotamu. Nekad. Tapi aku harus melakukannya.
Sampai di kotamu, aku segera
mengirimkan pesan singkat untukmu.
“Aku menunggumu di Jam Gadang.”
Tidak ada balasan darimu. Tapi aku yakin, kamu membaca pesanku dan
sedang menuju ke tempatku menunggu, di bawah jam kesayanganmu, Jam Gadang.
Lima belas menit, mungkin lebih, itu waktu yang aku habiskan untuk
menunggumu. Berjalan mengitari Jam Gadang, menatap jalan raya, meremas Rosario
yang selalu ada dalam sakuku, resah bersalut kerinduan yang membuncah.
Lima belas menit waktu yang aku habiskan sebelum mataku menangkap
sosokmu. Kamu yang tergesa berjalan menuju kearahku dengan jilbab marun yang
dipermainkan oleh angin.
“Mas kenapa kesini?” Itu kalimat pertamamu. Buyar semua bayanganku, aku
membayangkan bahwa pertemuan kita, setidaknya, akan diawali dengan kalimat
penuh rindu.
“Kamu ga kangen aku Dek?” Aku menyimpan kekecewaanku dan memilih untuk
menggodamu.
“Kangen.” Lirih.
Dan untuk pertama kalinya sejak aku menjalin kisah dengannya ada jeda
yang menggantung.
“Kamu apa kabar?” Ragu aku berusaha mengusir jeda.
“Mas ngapain ke sini?” Tajam, “Rere udah bilang, Bapak belum ngasih
lampu hijau!”
“Aku kangen Dek.”
Kamu membuang wajahmu, menatap jarum Jam Gadang yang terus berputar.
Meraih tangannya, “Aku capek nunggu Dek. BIar aku ketemu sama Bapak.
Biar Bapak ngeliat kalau Mas sungguh-sungguh sama kamu. Mas ga bisa nunggu
lebih lama.”
Perlahan gerimis turun. Tidak hanya awan yang meneteskan air, bola
matamu pun serta menitikkan air.
“Aku serius Dek. Sekalipun Bapak nuntut aku untuk mengikuti keyakin..”
Kamu meletakkan telunjukmu pada bibirku, mengisyaratkanku untuk diam.
“Aku ga mau ada pengorbanan Mas,” kamu tersenyum, mengusap air mata dan
mengambil sesuatu dari dalam tasmu.
TIN! TIIIIINNNN!!!
TIIINNNNNTINNNNNNN!!
Suara klakson panjang
mengembalikanku dari kenangan. Bukan Jam Gadang yang ada dihadapanku melainkan
Tugu Pancoran.
Melirik sekilas jok disampingku,
biasanya ada kamu disana.
Kosong.
Hanya ada secarik kertas
bernuansa emas dengan aksen marun yang mengisi jok itu. Kertas yang kemarin kamu berikan padaku dibawah gerimis di kotamu. Kertas yang mematri
namamu bersama dengannya, entah siapa. Seorang lelaki beruntung, sayang bukan aku.
Tidak ada lagi lampu hijau yang
harus aku tunggu.
Aku segera melajukan mobilku,
berusaha menghindari kemarahan dari para pengemudi yang tergesa. ***
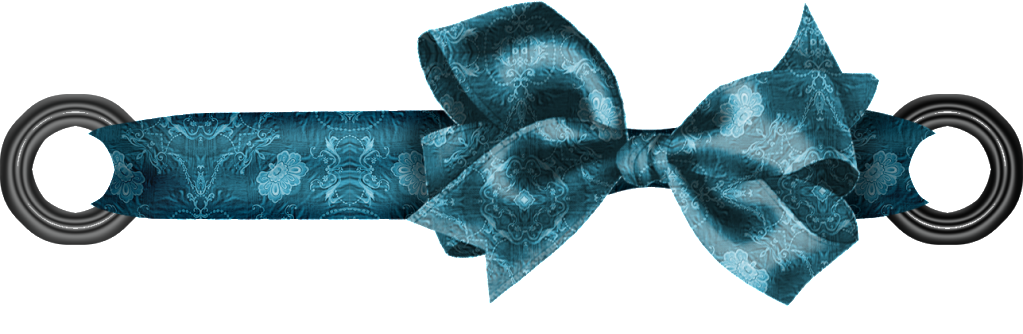

No comments:
Post a Comment