"Doyan banget ngopi," aku sengaja menggodanya, menggoda Sher adalah hobi baruku, "Kayak enggak ada minuman lain aja."
Bukannya menjawab pertanyaanku, Sher dengan santai menyesap kopinya. Aku hapal cara kesukaannya menikmati cairan hitam itu. Black, no sugar, no cream.
"Suka aja. Sama kayak kamu, minumnya teh mulu" dia meletakkan cangkirnya, "Enggak ada alasannya, kan, Bram?"
"Selalu ada alasan, Sher, selalu."
Dia kembali menyesap kopinya, "Kenapa ya? Mungkin karena aromanya, rasanya..apa ya? Enak aja, Bram. Enggak ada alasan khusus."
"Pahit gitu apa enaknya?" Aku kembali menggodanya.
"Justru karena pahitnya," Sher mengalihkan pandangannya ke luar jendela. Dan untuk sesaat aku seakan menangkap kehampaan pada sorotnya, "Semakin pahit, semakin aku suka."
"Ternyata kamu itu beneran aneh, ya?"
Dia tersenyum. Senyuman yang sangat jarang menghias wajahnya, "Karena pahit itu berarti biji kopinya di-roasting sampai benar-benar pekat. Mitosnya itu mengusir ketidakberuntungan. Dan hidupku penuh dengan ketidakberuntungan. Selain itu, pahitnya kopi bikin selalu ingat kalau sesempurna apapun hidup selalu ada pahit yang hadir."
"Ibra, Ibrahim?!" Mikha mengoyang lenganku pelan, "Kamu melamun?"
"Sorry," seketika ada rasa bersalah yang menyelinap masuk. Di saat aku sedang bersama dengannya, malaikatku, bagaimana mungkin aku memikirkan Sher?
"Enggak apa-apa. Kamu lagi banyak pikiran, ya? Kenapa? Ada masalah di kantor?"
"Enggak, eh, iya. Iya. Kerjaan kantor," aku salah tingkah.
"Jangan diforsir, Ibra. Kan kamu sendiri, kan, yang ngaku bukan workaholic karena kamu masih pengin nikmatin hidup kamu."
Aku membalas senyumnya, "Tenang aja. Ini juga, kan, aku lagi nikmatin hidup. Kencan sama kamu."
Dia tersipu dan berusaha menutupi pipinya yang memerah dengan menyesap kopinya, "Sejak kapan kita kencan?"
Giliran pipiku yang memerah. Ya. Sampai sekarang statusku dengan gadis ini hanya teman. Tidak lebih. Menyedihkan.
"Mikha, kenapa kamu suka kopi?" Aku asal bertanya untuk menutupi kecanggunganku.
"Hm, karena kopi itu kayak hidup."
"Emangnya hidup sepahit itu ya?" Kenapa setiap cewek yang dekat denganku menganalogikan hidup itu pahit seperti kopi?
"Bukan gitu, Ibra," dia menatapku lembut, "Gini, lho, hidup itu kayak kopi, plain, kita bisa bebas nambahin apa yang kita suka untuk bikin rasanya lebih menarik."
"Maksud kamu..?"
"Espresso, cappuchino, latte, semuanya itu kopi, kan? Tapi rasanya bisa beda banget, kan, padahal kita cuma sekadar nambahin susu atau coklatm kan? Gitu juga hidup. Hidup kita adonan dasarnya sama," dia membentuk tanda kutip dengan jarinya, "Gimana kitanya dan apa yang kita mau bikin hidup itu beda."
"Thoughtful."
"Kamu beneran enggak minum kopi, ya?"
"Bukan enggak minum, aku lebih prefer teh aja. Memangnya kenapa?"
"Enggak kenapa-kenapa. Cuma rasanya aneh aja di jaman sekarang ada yang enggak suka kopi."
"Pernah nyoba minum dan aku enggak suka rasanya. Jadi balik lagi ke teh."
Dia mengangguk paham lalu kembali menyesap kopinya, "Hari minggu ini kamu kosong enggak?"
"Belum tahu," aku mengambil smartphone dan mengecek jadwal, pagi aku harus menemani Papa golf dengan klien, "Kenapa?"
"Aku baru belajar masak dan butuh bantuan kamu untuk jadi komentator."
"Well, jadi buat kamu aku cuma kelinci percobaan?"
Dia tertawa, ritmis dan menular, "Itu cuma alasan aku aja," dia menunduk menatap halaman novel yang terbuka di hadapannya, "Sebenernya aku pengin masakin kamu tapi...malu bilangnya."
"Kamu ngajak aku nge-date?"
Matanya yang dibingkai bulu mata lentik menatapku terkejut. Beberapa kali dia mengerjapkan matanya. Cantik. Tidak. Lebih dari sekedar cantik. Dia sempurna.
"Bukan. Bukan gitu..aku cuma ngajak kamu makan siang." Dia salah tingkah.
"Kalau itu kencan aku bakalan datang. Tapi kalau bukan," aku menggelengkan kepala dengan dramatis, "Sorry, aku enggak bisa."
"Tapi..."
"Aku cuma mau dimasakin sama cewek yang statusnya pacar." Entah bagaimana dan entah keberanian dari mana kalimat itu terucap dari mulutku.
Dia kembali mengerjapkan matanya beberapa kali. Dan aku semakin kehilangan hatiku. Hatiku sempurna menjadi miliknya.
"Kamu..nembak aku?"
"Tergantung jawaban kamu."
Dia tersenyum malu dan aku tersenyum lebar.
"Jadi...?"
Dia mengangguk pelan.
Dan mendadak ada ratusan balon yang meledak di dadaku. Kebahagiaan. Sher, seandainya kamu ada di sini dan aku bisa membagi ini bersamaku, malam ini sempurna.
Ibrahim Wiranagara : Aku udah jadian sama Mikha
Ibrahim Wiranagara : Cepat pulang. Aku udah enggak sabar pengin ngenalin dia ke kamu.
Ibrahim Wiranagara : Safe trip. Jangan maksa.
Kali ini cawang dua.
Tapi sampai aku dan Mikha berpisah, cawang itu tidak juga berubah warna.
Bukannya menjawab pertanyaanku, Sher dengan santai menyesap kopinya. Aku hapal cara kesukaannya menikmati cairan hitam itu. Black, no sugar, no cream.
"Suka aja. Sama kayak kamu, minumnya teh mulu" dia meletakkan cangkirnya, "Enggak ada alasannya, kan, Bram?"
"Selalu ada alasan, Sher, selalu."
Dia kembali menyesap kopinya, "Kenapa ya? Mungkin karena aromanya, rasanya..apa ya? Enak aja, Bram. Enggak ada alasan khusus."
"Pahit gitu apa enaknya?" Aku kembali menggodanya.
"Justru karena pahitnya," Sher mengalihkan pandangannya ke luar jendela. Dan untuk sesaat aku seakan menangkap kehampaan pada sorotnya, "Semakin pahit, semakin aku suka."
"Ternyata kamu itu beneran aneh, ya?"
Dia tersenyum. Senyuman yang sangat jarang menghias wajahnya, "Karena pahit itu berarti biji kopinya di-roasting sampai benar-benar pekat. Mitosnya itu mengusir ketidakberuntungan. Dan hidupku penuh dengan ketidakberuntungan. Selain itu, pahitnya kopi bikin selalu ingat kalau sesempurna apapun hidup selalu ada pahit yang hadir."
Ini pertama kalinya Sher berbicara sepanjang ini. Biasanya dia hanya menjawab sekadarnya. Aku senang. Tapi kehampaan yang kembali hadir pada sorot matanya menusuk jantungku."
"Ibra, Ibrahim?!" Mikha mengoyang lenganku pelan, "Kamu melamun?"
"Sorry," seketika ada rasa bersalah yang menyelinap masuk. Di saat aku sedang bersama dengannya, malaikatku, bagaimana mungkin aku memikirkan Sher?
"Enggak apa-apa. Kamu lagi banyak pikiran, ya? Kenapa? Ada masalah di kantor?"
"Enggak, eh, iya. Iya. Kerjaan kantor," aku salah tingkah.
"Jangan diforsir, Ibra. Kan kamu sendiri, kan, yang ngaku bukan workaholic karena kamu masih pengin nikmatin hidup kamu."
Aku membalas senyumnya, "Tenang aja. Ini juga, kan, aku lagi nikmatin hidup. Kencan sama kamu."
Dia tersipu dan berusaha menutupi pipinya yang memerah dengan menyesap kopinya, "Sejak kapan kita kencan?"
Giliran pipiku yang memerah. Ya. Sampai sekarang statusku dengan gadis ini hanya teman. Tidak lebih. Menyedihkan.
"Mikha, kenapa kamu suka kopi?" Aku asal bertanya untuk menutupi kecanggunganku.
"Hm, karena kopi itu kayak hidup."
"Emangnya hidup sepahit itu ya?" Kenapa setiap cewek yang dekat denganku menganalogikan hidup itu pahit seperti kopi?
"Bukan gitu, Ibra," dia menatapku lembut, "Gini, lho, hidup itu kayak kopi, plain, kita bisa bebas nambahin apa yang kita suka untuk bikin rasanya lebih menarik."
"Maksud kamu..?"
"Espresso, cappuchino, latte, semuanya itu kopi, kan? Tapi rasanya bisa beda banget, kan, padahal kita cuma sekadar nambahin susu atau coklatm kan? Gitu juga hidup. Hidup kita adonan dasarnya sama," dia membentuk tanda kutip dengan jarinya, "Gimana kitanya dan apa yang kita mau bikin hidup itu beda."
"Thoughtful."
"Kamu beneran enggak minum kopi, ya?"
"Bukan enggak minum, aku lebih prefer teh aja. Memangnya kenapa?"
"Enggak kenapa-kenapa. Cuma rasanya aneh aja di jaman sekarang ada yang enggak suka kopi."
"Pernah nyoba minum dan aku enggak suka rasanya. Jadi balik lagi ke teh."
Dia mengangguk paham lalu kembali menyesap kopinya, "Hari minggu ini kamu kosong enggak?"
"Belum tahu," aku mengambil smartphone dan mengecek jadwal, pagi aku harus menemani Papa golf dengan klien, "Kenapa?"
"Aku baru belajar masak dan butuh bantuan kamu untuk jadi komentator."
"Well, jadi buat kamu aku cuma kelinci percobaan?"
Dia tertawa, ritmis dan menular, "Itu cuma alasan aku aja," dia menunduk menatap halaman novel yang terbuka di hadapannya, "Sebenernya aku pengin masakin kamu tapi...malu bilangnya."
"Kamu ngajak aku nge-date?"
Matanya yang dibingkai bulu mata lentik menatapku terkejut. Beberapa kali dia mengerjapkan matanya. Cantik. Tidak. Lebih dari sekedar cantik. Dia sempurna.
"Bukan. Bukan gitu..aku cuma ngajak kamu makan siang." Dia salah tingkah.
"Kalau itu kencan aku bakalan datang. Tapi kalau bukan," aku menggelengkan kepala dengan dramatis, "Sorry, aku enggak bisa."
"Tapi..."
"Aku cuma mau dimasakin sama cewek yang statusnya pacar." Entah bagaimana dan entah keberanian dari mana kalimat itu terucap dari mulutku.
Dia kembali mengerjapkan matanya beberapa kali. Dan aku semakin kehilangan hatiku. Hatiku sempurna menjadi miliknya.
"Kamu..nembak aku?"
"Tergantung jawaban kamu."
Dia tersenyum malu dan aku tersenyum lebar.
"Jadi...?"
Dia mengangguk pelan.
Dan mendadak ada ratusan balon yang meledak di dadaku. Kebahagiaan. Sher, seandainya kamu ada di sini dan aku bisa membagi ini bersamaku, malam ini sempurna.
Ibrahim Wiranagara : Aku udah jadian sama Mikha
Ibrahim Wiranagara : Cepat pulang. Aku udah enggak sabar pengin ngenalin dia ke kamu.
Ibrahim Wiranagara : Safe trip. Jangan maksa.
Kali ini cawang dua.
Tapi sampai aku dan Mikha berpisah, cawang itu tidak juga berubah warna.
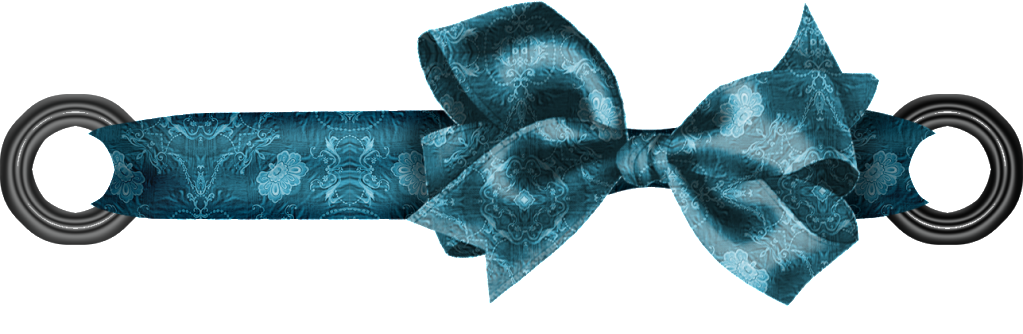

Kirain Sher-nya udh balik -_- ternyata ngayal. Haha buat Ibra, udh yakin nembak Sher? :p Buat kak dy, sorry baru baca skrg soalnya signal baru saja bersahabat dan ada bbrp typo, kak :D itu ajaa..
ReplyDeleteC.a. on de next episode 😄
Ibra nembak Sher? Ish, masih ngayal kayaknya :p
DeleteWaduh! typo tingkat galaksi bimasakti ini mah -______-
DeleteMaksudnya Ibra nembak Mbak Mimik, ituloh Mikha. *kemudian dibom sama pencipta karakternya :p
Mbak Mimik..yatallam..makin kece aja ini penyebutan namanya :p
DeleteIni namanya cinta datang terlambat *atau apalah* sebenernya mah Ibra, Bra, Bram itu sukanya sama Sher. Cuma dia gak cukup waras aja buat tau hal itu. HAHAHA *ditabok kak Dy*
ReplyDeletepada keukeh ya kalau Bram itu naksir Sher.
DeleteYa ampuuun...enggak cukup waras dong ya 😂😂😂
Jadian jadian jadiannnn asekkkk *muka sok polos
ReplyDelete